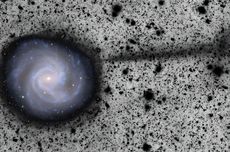INSIDEN di pertengahan November 2025 bukan sekadar "keseleo lidah" pejabat. Ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, di tengah acara Fun Run, berkeluh bahwa "jurnalisnya mingkem semua" sambil mengaitkannya dengan kesulitan ekonomi, kita sebenarnya sedang menyaksikan gejala klinis dari rapuhnya demokrasi.Ucapan itu bukan sekadar seloroh, melainkan semacam Freudian slip—pengakuan bawah sadar yang menyingkap jurang antara cara pandang elite dan kenyataan di akar rumput. Pernyataan Purbaya memicu apa yang bisa disebut "Demam Purbaya": kebingungan kolektif di mana penguasa menginginkan kritik sehat, tetapi tangan negara justru sibuk membungkam pengkritik.Pisau analisis psikologi politik dan sosiologi digital perlu dipakai untuk membedah mengapa pers tampak "mati suri" dan ke mana suara kritis itu bermigrasi.Baca juga: “Mingkemnya” Pers Disentil PurbayaDiagnosis Purbaya bahwa pers "mingkem" hanya separuh kebenaran. Dalam psikologi komunikasi, diam tidak selalu berarti setuju; sering kali itu adalah mekanisme bertahan hidup menghadapi ancaman eksistensial. Ketika jurnalis berhadapan dengan risiko kriminalisasi atau serangan doxing, naluri reptil mereka memilih bertahan: diam di permukaan. Namun suara itu tidak lenyap.Mengacu pada konsep James C. Scott tentang Hidden Transcripts, kritik yang dibungkam di panggung resmi akan berpindah ke panggung belakang. Di Indonesia 2025, panggung belakang itu adalah "Ruang Publik Bayangan": diskursus kritis bergeser dari editorial koran ke grup WhatsApp tertutup, kanal Telegram terenkripsi, dan komunitas dark social.Ironinya, Purbaya tidak mendengar kritik bukan karena tak ada, melainkan karena ia tak punya akses ke crypto-publics ini. Teori Habermas tentang ruang publik rasional runtuh, digantikan oleh echo chambers yang terfragmentasi. Di ruang gelap ini, kritik kehilangan standar verifikasi jurnalistik, berubah menjadi rumor dan kemarahan tak terarah. Ketakutan negara terhadap "gangguan stabilitas" justru melahirkan instabilitas yang lebih sulit dipantau.Ketika pers arus utama dipaksa menjadi humas istana, negara kehilangan cermin jujur untuk menatap wajahnya sendiri. Akibatnya, kebijakan ekonomi—seperti penanganan utang Whoosh atau anggaran daerah—menjadi buta terhadap realitas lapangan.Baca juga: Demam Purbaya dan Sentilan Pers Mingkem: Pelajaran dari Masa LaluPernyataan Purbaya yang menyalahkan kebisuan pers sebagai penyebab "ekonomi susah" adalah bentuk klasik mekanisme pengambinghitaman. Rene Girard menjelaskan bahwa ketika sebuah masyarakat menghadapi krisis internal, mereka cenderung mencari korban untuk dipersalahkan demi memulihkan kohesi semu. Dalam konteks ini, pers dijadikan tumbal.Padahal, inefisiensi anggaran daerah sebesar Rp254 triliun yang mengendap adalah masalah birokrasi, bukan jurnalistik. Tetapi secara psikologis, lebih mudah menyalahkan "pembawa pesan" daripada memperbaiki "isi pesan".Fenomena ini diperkuat oleh "Nostalgia Represif". Pemberian gelar pahlawan kepada tokoh otoritarian masa lalu bukan sekadar rekonsiliasi sejarah, melainkan upaya membangkitkan memori kolektif tentang "ketertiban" untuk melegitimasi kontrol hari ini. Psikologi memori kolektif mencatat bahwa nostalgia sering manipulatif: ia menghapus trauma dan hanya menyisakan kenangan tentang stabilitas harga.Narasi "pelajaran dari masa lalu" dipakai bukan untuk menghindari kesalahan sejarah, melainkan untuk menormalisasi tangan besi. Kita ditarik mundur ke era di mana ketakutan dianggap syarat pembangunan, sebuah regresi psikologis yang menghambat inovasi bangsa.Baca juga: Mengingat Sejarah Kelam Kebebasan Pers di Indonesia Era SoehartoJika represi masa lalu menggunakan senapan, represi kini menggunakan algoritma. Kita bergeser dari otoritarianisme negara ke Algorithmic Governmentality. Kontrol tak lagi butuh aparat di setiap sudut, melainkan tertanam dalam kode platform digital yang mengatur visibilitas konten. Paradoks ini tampak jelas saat perayaan Sumpah Pemuda. Tema "Pemuda Pemudi Bergerak" di tahun 2025 bertabrakan dengan penangkapan ribuan demonstran muda.Lahir "Nasionalisme Digital Paradoksal": pemuda didorong merayakan identitas bangsa di media sosial, tetapi dikriminalisasi saat mempraktikkan esensi Sumpah Pemuda, yakni keberanian politik.Keberadaan "Polisi Virtual" dan kebijakan take-down konten menciptakan Panoptikon digital. Warga mendisiplinkan diri sendiri karena merasa selalu diawasi algoritma. Influencer yang menolak regulasi pun akhirnya tunduk demi engagement. Akibatnya, muncul "Keletihan Demokrasi". Generasi muda, yang seharusnya motor kritik, terjangkit Learned Helplessness: kondisi di mana seseorang merasa apa pun yang dilakukan tak akan mengubah hasil, sehingga memilih pasif dan apatis.Baca juga: Tepis Isu Pembungkaman Pers, Kemenko Polkam Beberkan Alasan Kebijakan Take Down PemberitaanMendiagnosis penyakit hanyalah langkah awal; kita butuh intervensi konkret untuk menyembuhkan "Demam Purbaya" dan memulihkan kewarasan publik. Solusi harus menyentuh akar psikologis dan struktural:Sebagai penutup, Purbaya dan kabinetnya perlu memahami hukum psikologi dasar: rasa aman adalah prasyarat kejujuran. Anda tak bisa meminta orang berbicara lantang sambil menodongkan senjata—baik senjata api maupun pasal hukum—ke kepalanya.Jika pemerintah ingin pers "tidak mingkem" agar ekonomi selamat, maka tangan yang memegang pentungan harus diturunkan terlebih dahulu. Hanya dalam ekosistem bebas dari rasa takutlah solusi cerdas bagi masalah ekonomi bangsa bisa lahir. Tanpa itu, keheningan akan terus menjadi jeritan yang memekakkan telinga di ruang-ruang tak terjamah kekuasaan, menunggu saat untuk meledak.
(prf/ega)
Mendiagnosis Keheningan Pers: Sebuah Autopsi Psikologis
2026-01-12 04:25:55

Berita Lainnya
Berita Terpopuler
| 2026-01-12 04:23
| 2026-01-12 03:23
| 2026-01-12 03:07
| 2026-01-12 02:41
| 2026-01-12 02:32