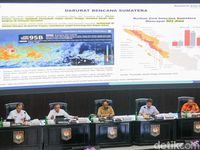MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyentil pers yang “mingkem”, tidak berani melontarkan kritik kepada pemerintah. Kritik itu disampaikan Purbaya dalam acara yang digelar Forum Pemimpin Redaksi di Jakarta, Minggu 16 November 2025.Kritik Purbaya ini menarik dan mengandung separuh kebenaran. PK Ojong punya pandangan yang senada. Pers dibuat bukan untuk menjilat kekuasaan. Kritik pers memang dibutuhkan karena kekuasaan itu cenderung korup. Pada saat ini, kritik pers justru amat dibutuhkan ketika bangsa sedang mengalami krisis representasi. DPR mengalami apa yang disebut Carl Schmitt sebagai telah kehilangan dasar moral dan spiritualnya. Itu ditulis Schmitt dalam buku The Crisis of Parliamentary Democracy, 1923. Selain pers yang “mingkem", DPR, DPD, ormas pun sebenarnya “mingkem” melihat praktik politik penuh ketidakadilan. Dalam bahasa pemikir kebhinekaan, Sukidi, bangsa sedang dibangun dalam situasi republik ketakutan (republic of fear).Gejala pers yang “mingkem” sudah ditengarai Daniel Dhakidae dalam disertasinya di Cornel tahun 1991. Dalam disertasi The State, the Rise of Capital, and the Fall of Political Journalism: Political Economy of Indonesian News Industry, Daniel memprediksi sistem pers Orde Baru dengan kontrol kertas di tangan pemerintah akan menciptakan situasi menjadi akhir dari jurnalisme politik (the end of political journalism).Kritik Purbaya disebut sebagai separuh kebenaran karena sebenarnya ada juga pers, katakan Tempo, yang berani mengkritik pemerintahan secara lugas dan tegas terhadap tata kelola pemerintahan. Namun kini, Tempo tengah menghadapi gugatan ganti rugi Rp 200 miliar oleh Menteri Pertanian. Bisa saja pandangan Purbaya adalah pandangan pribadi seorang menteri berbeda dengan menteri yang lain.Dalam praktik selama ini, dalam lingkungan komunitas pers, tertangkap suasana kebatinan bahwa pemerintah lebih suka dengan berita-berita positif, terlebih pujian. Dalam beberapa kejadian selalu ada upaya tangan tak kelihatan untuk mengendalikan pers bebas yang memang sedang dalam tahapan survival mode. “Padahal, pujian adalah silent killer,” kata Sukidi, dalam sebuah pernyataan di Forum Warga Negara.Ini berbeda misalnya dengan pandangan Ali Sadikin. Ali Sadikin dalam satu wawancara pernah mengatakan, “… wartawan itu karyawan pemerintah yang tidak dibayar negara. Tugasnya justru mengkritik kebijakan pemerintah….,” kata Ali Sadikin.Tapi apakah pejabat kita seterbuka Ali Sadikin menerima kritik dari media sebagaimana disampaikan Purbaya.Baca juga: Mengingat Sejarah Kelam Kebebasan Pers di Indonesia Era SoehartoSejak lama, media disebut sebagai pilar keempat demokrasi— the fourth estate—setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Media dimandatkan untuk mengawasi kekuasaan, menyediakan informasi publik, dan menjadi forum deliberasi bagi warga negara.Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam The Elements of Journalism menulis: “Kewajiban pertama jurnalisme adalah kepada kebenaran, dan kesetiaan pertamanya adalah kepada warga.” Namun kini, secara umum posisi media itu goyah. Bukan karena hilangnya idealisme, tetapi karena dua tekanan besar: krisis ekonomi di dalam industri media, dan dominasi algoritma di luar ruang redaksi. Media berdiri di persimpangan: antara bisnis dan etika, antara klik dan kebenaran.Industri media kini menghadapi guncangan struktural yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendapatan iklan berpindah ke platform digital seperti Google, Meta, dan TikTok. Ruang redaksi kehilangan kemandirian ekonomi, sementara pemilik modal semakin berkuasa menentukan arah pemberitaan. Robert McChesney menyebut fenomena ini sebagai market censorship— sensor pasar—di mana bukan negara yang menekan kebebasan pers, tetapi logika bisnis yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan.Konsentrasi kepemilikan membuat media kerap kehilangan keberanian moral. Liputan investigative berkurang. Isu publik tergantikan oleh sensasi politik. Kecenderungan media menjadi pelapor fakta. Namun, tentunya masih ada media yang mencoba menjalankan jurnalisme advokatif.Selain krisis ekonomi, kita juga menghadapi krisis suara. Manuel Castells, dalam Communication Power, mengatakan: “Kekuasaan di era informasi adalah kekuasaan untuk memprogram arus komunikasi.”Buzzer politik, influencer, dan mesin algoritma kini bertindak sebagai “editor baru” ruang publik. Mereka menentukan apa yang trending, bukan apa yang penting. Mereka menyebarkan emosi, bukan pengetahuan. Kita hidup dalam demokrasi simulatif: terlihat ramai, tapi kehilangan kedalaman. Setiap warga seolah punya suara, tapi suara-suara itu dikendalikan oleh kekuatan yang tak terlihat— oleh mesin, oleh modal, oleh kepentingan politik. Buzzer telah menjadi industri. Tapi apakah itu kebenaran? Belum tentu.
(prf/ega)
“Mingkemnya” Pers Disentil Purbaya
2026-01-11 03:34:52

Berita Lainnya
Berita Terpopuler
| 2026-01-11 03:29
| 2026-01-11 02:43
| 2026-01-11 02:28
| 2026-01-11 02:28
| 2026-01-11 02:20