ADA satu penyakit lama dalam kepemimpinan Indonesia yang tidak pernah benar-benar sembuh. Penyakit ini tidak selalu terlihat, tidak selalu bersuara, tetapi dampaknya merusak dari dalam.Ia bekerja pelan, sistemik, dan sering kali justru dianggap “biasa”. Penyakit itu bernama mentalitas asal bos senang (ABS) atau dalam bahasa yang lebih populer, asal bapak senang, asal ibu senang.Penyakit ini bukan sekadar soal etika birokrasi. Ia bukan hanya tentang bawahan yang gemar menyenangkan atasan. Lebih dari itu, mentalitas asal bos senang adalah bom waktu kepemimpinan.Ia menciptakan ilusi keberhasilan, menumpulkan kepekaan pemimpin, dan pada akhirnya menjauhkan negara dari realitas rakyatnya sendiri.Indonesia hari ini sedang berdiri di persimpangan penting. Di satu sisi, bangsa ini memiliki potensi besar, bonus demografi, kekuatan ekonomi kreatif, sumber daya manusia muda yang semakin kritis, serta posisi geopolitik strategis.Namun di sisi lain, kemarahan rakyat juga sedang mengendap, pelan tapi pasti. Ia muncul dalam bentuk sinisme publik, ketidakpercayaan pada elite, kemarahan di media sosial, demonstrasi jalanan, hingga apatisme politik yang makin meluas.Masalahnya bukan karena rakyat Indonesia tidak sabar. Masalahnya adalah karena terlalu lama rakyat merasa tidak didengar.“Man is by nature a political animal,” seperti yang sering disampaikan Aristoteles. Pesan ini menegaskan bahwa manusia berinteraksi dalam ruang publik, sehingga keterbukaan dan dialog adalah sifat fundamental kepemimpinan yang sehat.Baca juga: Kiamat Pencitraan: Warganet Kini Vs Pemimpin Tipu-tipuKesenjangan antara narasi resmi dan realita sehari-hari inilah yang membuat rakyat frustrasi. Kemarahan publik adalah akumulasi dari kekecewaan terhadap pemimpin yang dirasa gagal mengerti dan memenuhi kebutuhan mereka.Pengamat politik Rocky Gerung mengingatkan, dalam demokrasi pemerintah semestinya tunduk pada rakyat, bukan sebaliknya.Salah satu ironi terbesar dalam kepemimpinan adalah ketika seorang pemimpin merasa aman justru saat ia berada dalam bahaya. Mentalitas asal bos senang menciptakan kondisi ini dengan sempurna.Di hadapan pemimpin, laporan terlihat rapi. Angka-angka tampak positif. Grafik naik. Target seolah tercapai. Namun di lapangan, rakyat bergulat dengan realitas yang jauh berbeda.Harga kebutuhan pokok naik, tetapi laporan inflasi dikemas seolah terkendali. PHK terjadi di mana-mana, tetapi data ketenagakerjaan ditampilkan normatif.Daya beli melemah, tetapi pidato-pidato resmi tetap optimistis. Ketimpangan melebar, namun narasi keberhasilan terus diulang.Di sinilah bahayanya. Pemimpin yang dikelilingi oleh orang-orang yang hanya ingin menyenangkan, sesungguhnya sedang dibutakan secara sistematis.Dalam teori kepemimpinan modern, ini dikenal sebagai 'information distortion'. Ketika informasi yang sampai ke pemimpin sudah “dipoles”, maka keputusan yang diambil pun berangkat dari asumsi yang salah.Dan keputusan yang salah, dalam skala negara, berdampak langsung pada jutaan nyawa dan masa depan bangsa.Jim Collins, dalam Good to Great, menegaskan bahwa organisasi hebat dibangun oleh pemimpin yang berani “menghadapi fakta brutal” (confront the brutal facts).Tanpa keberanian menghadapi kenyataan, organisasi termasuk negara akan runtuh oleh kesalahan yang tidak pernah diakui.Sayangnya, mentalitas asal bos senang justru melakukan kebalikannya, menyembunyikan fakta brutal demi kenyamanan jangka pendek.Ada paradoks besar dalam budaya asal bos senang, ia tampak melindungi pemimpin, padahal sejatinya membahayakan pemimpin itu sendiri.Pemimpin yang tidak diberi tahu kondisi sebenarnya akan kehilangan kemampuan membaca situasi. Ia terlambat mengantisipasi krisis. Ia salah mengukur risiko. Ia keliru menentukan prioritas. Dalam konteks politik dan pemerintahan, ini sangat fatal.Sejarah memberi banyak pelajaran. Banyak rezim runtuh bukan karena kurang kekuasaan, tetapi karena terlalu lama hidup dalam gelembung pujian.Mereka tidak melihat tanda-tanda ketidakpuasan rakyat, karena tanda-tanda itu tidak pernah sampai ke meja kekuasaan.Budaya asal bos senang membuat bawahan takut menyampaikan kabar buruk. Padahal dalam kepemimpinan sejati, kabar buruk justru adalah aset paling berharga. Ia menjadi bahan pembelajaran, dasar perbaikan, dan alarm dini untuk perubahan.Baca juga: Antara Capek Cari Kerja dan Capek Melimpah JabatanPeter Drucker pernah mengatakan, “The most dangerous thing in times of turbulence is not the turbulence; it is to act with yesterday’s logic.”Dalam konteks Indonesia, logika lama itu adalah keyakinan bahwa stabilitas bisa dijaga dengan menutup masalah dan membungkus realitas.Padahal dunia sudah berubah. Rakyat sudah berubah.Hari ini, rakyat Indonesia jauh lebih kritis. Media sosial, jurnalisme warga, dan keterbukaan informasi membuat realitas tidak bisa lagi dimonopoli oleh elite.Ketika data resmi mengatakan “semua baik-baik saja”, rakyat membandingkannya dengan pengalaman hidup mereka sendiri.
(prf/ega)
Mengakhiri Budaya Pujian: Asal Rakyat Senang, Negara Tenang
2026-01-12 04:56:57
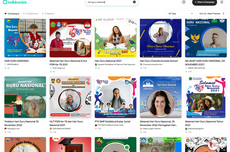
Berita Lainnya
Berita Terpopuler
| 2026-01-12 05:01
| 2026-01-12 04:50
| 2026-01-12 04:30
| 2026-01-12 04:18
| 2026-01-12 03:06


















































