KASUS perundungan terhadap siswa SMP di Grobogan dan mahasiswa Udayana belakangan ini, menyingkap sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kekerasan antarindividu.Ia membuka wajah gelap dari cara kita mendidik anak laki-laki untuk menjadi “jantan”—suatu konsep yang dibentuk oleh ideologi kekuasaan, bukan oleh kemanusiaan.Ketika seorang siswa diejek “wadon” hanya karena tidak melawan balik, atau seorang mahasiswa dengan gangguan pendengaran dirundung karena “berbeda”, keduanya menunjukkan pola yang sama: bahwa dalam tatanan sosial kita, menjadi lembut, rentan, atau tidak sesuai dengan standar maskulinitas dominan adalah bentuk “penyimpangan” yang pantas dihukum secara simbolik maupun fisik.Fenomena ini bukanlah sekadar perilaku salah individu, melainkan gejala struktural dari apa yang disebut para teoretikus gender sebagai toxic masculinity—maskulinitas beracun.Konsep ini pertama kali dikembangkan dalam kajian psikologi sosial untuk menjelaskan bentuk-bentuk perilaku laki-laki yang menindas diri mereka sendiri dan orang lain demi menegakkan ideal kejantanan yang tak realistis: kuat, tak berperasaan, dominan.Baca juga: Negara dan Generasi Teror 72Dalam masyarakat patriarkal, laki-laki didorong untuk menekan emosi, menghindari kelembutan, dan membuktikan diri lewat agresi atau kontrol terhadap yang dianggap lemah.Di ruang sekolah maupun kampus, ideologi ini bekerja dalam mekanisme sehari-hari berbentuk ejekan, pengucilan, kekerasan fisik, dan pelabelan.Dalam kasus SMP Geyer, kata “wadon” bukan sekadar umpatan. Ia adalah kode sosial yang menunjukkan bahwa perempuan (atau sifat-sifat feminin) dianggap lebih rendah.Dengan memanggil seseorang “wadon”, pelaku bullying sedang menegakkan tatanan patriarki dengan menandai dirinya sebagai laki-laki sejati, dan korban sebagai yang gagal menjadi jantan.Sosiolog Raewyn Connell, dalam Masculinities (1995), menyebut hal ini sebagai “hegemonic masculinity”: tatanan nilai yang menempatkan satu bentuk maskulinitas (kuat, dominan, heteroseksual) sebagai standar ideal, sementara bentuk-bentuk maskulinitas lain (seperti yang lembut, ekspresif, atau tidak agresif) dipinggirkan.Dalam konteks Indonesia, bentuk hegemoni ini diperkuat oleh warisan budaya yang masih menautkan kejantanan dengan kekuasaan atas tubuh dan ruang sosial: bahwa “laki-laki harus kuat”, “laki-laki tidak boleh menangis”, “laki-laki pemimpin”.Namun, sebagaimana dikritik oleh penulis dan psikoterapis Ester Lianawati dalam bukunya Akhir Penjantanan Dunia (2022), sistem penjantanan semacam ini adalah jebakan yang melukai dua arah: ia menindas perempuan sekaligus membungkam laki-laki.Lianawati menulis, kejantanan yang beracun membuat laki-laki kehilangan kemampuan berempati, sebab sejak kecil mereka diajari bahwa kelembutan adalah kelemahan. Akibatnya, kekerasan dianggap wajar, bahkan perlu, demi mempertahankan status maskulin.Kita melihat logika ini bekerja di berbagai ruang. Dalam kasus mahasiswa Udayana, misalnya, korban perundungan adalah individu dengan gangguan pendengaran dan kecenderungan neurodivergen. Bullying terhadapnya bukan sekadar karena ia “berbeda”, tetapi karena ia tidak sesuai dengan skrip sosial tentang bagaimana seorang laki-laki harus bertingkah: tegas, percaya diri, tangguh.
(prf/ega)
Hegemoni Maskulinitas dan Luka Sosial Kita
2026-01-12 06:50:54

Berita Lainnya
Berita Terpopuler
| 2026-01-12 06:48
| 2026-01-12 06:34
| 2026-01-12 05:57
| 2026-01-12 04:22













































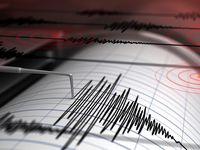
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5438384/original/025038500_1765286261-1000630284.jpg)


