BANJIR bandang dan longsor yang menghantam pulau Sumatra pada akhir November 2025 — dari Aceh hingga Sibolga dan berbagai titik di Sumatera Barat dan Sumatera Utara — menyisakan luka yang dalam. Menurut data terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban tewas telah mencapai 442 orang dan ratusan lainnya hilang.Pada 30 November 2025, angka resmi menunjukkan 442 kematian, dengan 402 orang masih hilang, sementara ribuan rumah hancur atau terendam, dan ratusan ribu orang mengungsi (BNPB, 2025; Reuters, 2025; AP, 2025).Jika dibaca sekilas, mudah bagi kita untuk menilai peristiwa semata sebagai akibat “curah hujan ekstrem” atau pengaruh siklon tropis yang jarang terjadi di Selat Malaka. Memang, faktor atmosferik seperti anomali monsun atau siklon (dikenal media sebagai Cyclone Senyar) memperkuat curah hujan.Namun membaca banjir hanya sebagai fenomena meteorologis mengaburkan gambaran yang lebih besar bahwa banjir ini muncul di atas lanskap yang telah mengalami perubahan fungsi dan degradasi ekologis dalam skala luas — bahwa bencana ini harus dibaca sebagai produk dari transformasi ekologi dan politik — sebuah tragedi struktural yang lahir dari relasi kuasa atas ruang, modal, dan regulasi.Maka penting untuk meminjam lensa ekologi politik bagaimana keputusan investasi, alih fungsi lahan, dan relasi kuasa korporasi–negara mencipta kerentanan struktural yang mematikan.Baca juga: Banjir di Aceh dan Sumatera, WALHI Soroti Deforestasi 1,4 Juta Hektar dan Krisis IklimBeberapa studi yang menggabungkan pengukuran hidrologi, analisis laju alih guna lahan, dan pengetahuan lokal menemukan bahwa peningkatan aliran permukaan dan penurunan kemampuan infiltrasi tanah setelah konversi hutan ke perkebunan menjadi penyumbang penting meningkatnya kejadian banjir di lembah-lembah sungai setempat (Merten et al., 2020).Selain itu, analisis nasional dan peta perubahan tutupan lahan menegaskan bahwa ekspansi perkebunan sawit telah menggantikan jutaan hektar hutan, mengikis kapasitas lanskap untuk menahan air hujan secara alami (Gaveau et al., 2022).Hal ini menunjukkan hubungan yang jelas antara konversi hutan menjadi perkebunan monokultur (khususnya kelapa sawit dan karet) dengan perubahan fungsi hidrologis sungai dan cekungan air, yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi dan intensitas banjir.Merujuk pada data Global Forest Watch (2024) ditarik dalam rentang dua dekade lebih (2001 - 2024), peta hijau Pulau Sumatra mengalami pengikisan yang berkelanjutan yang menandai perubahan fungsi lanskap secara sistemik.Di pesisir utara, Sumatera Utara tercatat kehilangan sekitar 1,6 juta hektare tutupan pohon antara 2001 - 2024. Di Sumatera Selatan kehilangan sekitar 3,3 juta hektare, menandai tekanan intens pada hutan primer dan sekunder yang sebelumnya menyokong fungsi ekologis regional — dari penahan banjir hingga penyediaan habitat dan jasa ekosistem.Sementara itu, Sumatera Barat yang pegunungannya sensitif terhadap erosi melaporkan kehilangan sekitar 740.000 hektare, sebuah angka yang mencerminkan berkurangnya penutup vegetasi di lereng-lereng yang krusial bagi stabilitas tanah dan pencegahan longsor.Sedangkan pada tahun 2024 saja, melalui analisis satelit dan pelaporan investigatif menunjukkan bahwa Sumatra kehilangan sekitar 91.248 hektare, artinya ada kenaikan hampir tiga kali lipat pembukaan lahan perkebunan dan pembersihan legal di dalam izin konsesi di tahun 2023 (Mongabay, 2025).Data ini memperkuat studi kualitatif yang dilakukan tim peneliti dari University of Göttingen bahwa ekspansi perkebunan sawit dan karet meningkatkan frekuensi dan intensitas banjir, perubahan penggunaan lahan mengubah sifat tanah dan permukaan daratan, mengurangi kemampuan infiltrasi air serta meningkatkan limpasan permukaan (Merten, J., et al.,2020)..Sementara tutupan vegetasi alami (yang menyerap dan menahan air) hilang atau berubah fungsi, menyebabkan hujan lebat — terutama saat siklon tropis atau anomali monsun — mudah berubah menjadi bencana.Banyak kawasan yang dulunya berfungsi sebagai “sponge” alam kini telah berubah menjadi lahan agribisnis, dengan drainase buatan dan struktur tanah yang lebih padat. Kombinasi ini mempercepat aliran air ke hilir saat hujan deras. Maka banjir Sumatera tahun ini adalah gejala serius dari akumulasi kesalahan — sebuah “erosi ekologi” yang berlangsung panjang.Baca juga: Prabowo ke Korban Banjir di Padang: Kalian Suka Enggak kalau Saya Sikat Itu Maling Semua?
(prf/ega)
Relasi Kuasa di Balik Bencana Banjir Sumatera
2026-01-12 07:37:57

Berita Lainnya
Berita Terpopuler
| 2026-01-12 07:24
| 2026-01-12 07:22
| 2026-01-12 06:39
| 2026-01-12 06:20
| 2026-01-12 05:46















































:strip_icc()/kly-media-production/medias/5426791/original/024464800_1764317618-8.jpg)

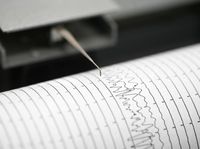
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5443316/original/082166600_1765679268-Nanik.jpeg)